Catatan Awal: Tulisan ini merupakan seri keempat dari lima tulisan saat mengunjungi pameran Mia Bustam: Karya, Kehidupan, Pemikiran di Benteng Vredeburg Yogyakarta (dalam rangka Biennale Jogja XVIII) pada 6 Oktober sampai dengan 20 November 2025.
Jujur saja, ada yang aneh saat pertama kali melangkah ke pameran Mia Bustam di Benteng Vredeburg. Ekspektasi saya soal galeri seni langsung buyar. Saya datang mencari seni, tapi yang saya temukan adalah sebuah ruang kosong yang justru penuh sesak dengan makna. Ruangan ini tidak menyambut dengan keindahan. Sebaliknya, terasa seperti sebuah monumen duka yang sengaja dibangun di atas luka lama sebab Mia bustam pernah ditahan di Benteng Vredeburg. Pameran ini merayakan seorang seniman justru dengan memamerkan kehancuran warisannya. Dan di situlah saya sadar, ini bukan kunjungan biasa. Hal ini adalah konfrontasi karena pameran ini bukanlah sekadar kunjungan yang pasif dan menyenangkan untuk melihat keindahan (seperti pameran seni pada umumnya). Sebaliknya, pameran ini secara aktif memaksa pengunjung untuk berhadapan langsung dengan beberapa hal yang sulit dan tidak nyaman. Dengan sejarah yang hilang, dengan perasaan yang dipendam, dan dengan kekuasaan yang seenaknya menghapus cerita seseorang. Esai ini untuk jujur pada diri sendiri, mengurai apa yang saya rasakan saat berjalan melewati reruntuhan ingatan itu dan dipaksa untuk ikut merasakan kehilangan. Ini adalah sebuah pengakuan, kesaksian personal tentang bagaimana seni, bahkan dalam ketiadaannya, bisa menampar kita dengan kebenaran yang paling pahit.
Ditarik ke Dalam Luka
Terdapat dua instalasi yang seolah saling berbicara dalam bahasa kerapuhan dan kekerasan. Keduanya menghantam saya dengan cara yang berbeda namun saling melengkapi, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang membekas lama setelah saya meninggalkan ruangan.

Gambar 1. Nessa Theo, The Other Side of Melancholia (2025)
Yang pertama adalah instalasi yang menggabungkan lukisan Mia dengan arsip kehidupannya. Di antara benda-benda yang tampak sunyi, justru karya Nessa Theo yang berjudul The Other Side of Melancholia (2025) inilah yang paling gaduh. Bukan oleh suara, melainkan oleh ingatan yang tumpah. Lukisan anak-anak dengan tatapan polos itu tergantung di dinding merah marun yang membuat ruangan seolah berdenyut. Namun dari bawah bingkainya, lembaran-lembaran kertas tua mengalir seperti air yang tak bisa ditahan, berjatuhan hingga ke lantai. Saya spontan berhenti. Ada sesuatu yang menekan dada saya semacam rasa tidak nyaman, seperti sedang memandangi luka yang dibiarkan terbuka. Saya berjongkok mendekat, melihat tinta tua. Di situ saya sadar, kertas-kertas itu bukan dekorasi. Itu salinan surat, catatan, dan fragmen kehidupan pribadi. Melihatnya berserakan membuat saya merasa bersalah, seperti sedang menginjak kenangan seseorang. Arsip yang tumpah itu bukan sekadar benda, seperti tubuh yang sudah tak mampu lagi menahan beban sejarahnya. Saya terdiam cukup lama, menatap tumpukan kertas itu sambil berpikir, berapa banyak kisah yang harus retak dulu sebelum bisa dipahami orang lain?
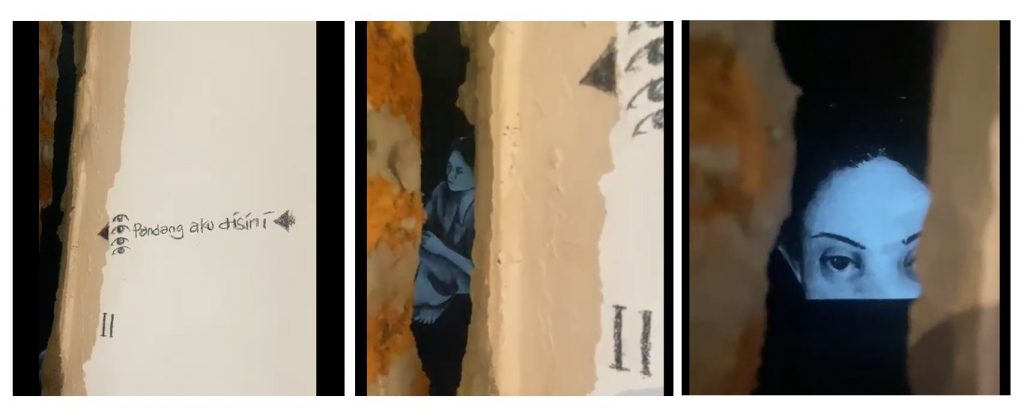
Gambar 2. Chandra Rosselinni, Bayang di Balik Tembok (2025)
Sebuah dinding putih dengan retakan yang sengaja dibuat. Dari celahnya yang gelap, saya melihat tulisan kecil, hampir seperti catatan rahasia “Pandang aku di sini.” Saya menunduk, mendekat, lalu berjongkok untuk mengintip. Gerakan tubuh itu saja sudah membuat saya merasa seperti sedang melanggar sesuatu. Di dalam gelap, muncul video hitam-putih potongan wajah dan tubuh perempuan yang bergerak perlahan. Saya merasa canggung, hampir ingin mundur. Sensasi dingin menjalar dari lantai ke telapak kaki, dan saya menyadari betapa sunyinya ruang itu. Piano masih terdengar lembut, tapi kini setiap nada terasa seperti tarikan napas terakhir. Dalam momen itu, saya tak lagi merasa sedang melihat seni. Saya sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam sebuah kerentanan yang tidak dibuat untuk dipertontonkan. Ketika akhirnya saya berdiri lagi, pandangan saya tertumbuk pada retakan di dinding itu.
Di sanalah, melalui retakan dalam karya Chandra Rosselinni berjudul Bayang di Balik Tembok (2025) tersebut, saya merasa Mia bukan hanya pelukis, tapi sosok yang bertahan di antara luka dan keberanian. Retakan itu bukan sekadar simbol kehancuran, melainkan cara lain untuk tetap bisa bicara ketika dunia menutup telinga. Saya keluar dari ruangan dengan langkah pelan, masih membawa rasa bersalah, iba, dan kagum yang saling bertumpuk. Di luar, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya atau mungkin memang saya yang belum pulih dari apa yang baru saya alami. Dalam hati saya berpikir, mungkin inilah yang disebut kejujuran dalam seni, ketika karya tak lagi bisa dipisahkan dari tubuh dan sejarahnya, dan kita penonton tak punya pilihan lain selain ikut terluka sedikit.
Saat Teori Tak Lagi Terasa Jauh
Awalnya saya bingung bagaimana harus memaknai semua ini. Tapi kemudian saya teringat gagasan Walter Benjamin tentang konsep aura. Menurut Benjamin (1968), aura merupakan semacam pesona magis yang hanya dimiliki oleh karya seni asli, yaitu pesona yang muncul karena keunikan, keotentikan, dan sejarah yang dimilikinya sendiri. Apa yang dilakukan Orde Baru pada 1965 bukan cuma membakar lukisan. Mereka melakukan pembunuhan terhadap aura. Sebuah pemusnahan yang disengaja terhadap jejak seorang seniman dalam tradisi dan sejarah. Dan pameran ini, dengan sangat berani, tidak mencoba menghidupkannya kembali. Ia tidak berpura-pura. Perlawanan pameran ini adalah dengan menciptakan aura baru. Bukan aura lukisan, tapi aura kesaksian yang terpancar dari setiap sobekan surat dan arsip. Aura ini tidak lahir dari keindahan, tapi dari keberanian untuk tetap ada meski dalam bentuk serpihan. Justru karena reproduksi itu terasa kurang menjadi bukti paling kuat dari kejahatan yang telah terjadi.
Lalu bagaimana bisa pameran yang begitu kelam ini justru terasa membebaskan? Marcuse (1978) menjelaskan bahwa utopia estetis menyajikan sebuah dunia lain yang melawan kenyataan yang menindas. Pameran ini melakukan hal itu. Hal ini mengubah fakta sejarah yang menjadi sebuah pengalaman puitis. Instalasi dinding retak atau tirai kain itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah cara untuk membuat kita merasa terasing dari cara pandang sejarah yang kaku. Kita dipaksa keluar dari kepala dan masuk ke dalam perasaan. Di dalam galeri ini, Mia Bustam bukan lagi korban, 1a adalah subjek yang utuh: pemikir, ibu, seniman. Harapan yang ditawarkan bukan janji kosong, tapi sebuah tuntutan moral dimana keadaan harus berubah. Utopia disini bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah cara pandang baru yang lahir dari reruntuhan.
Terapi di Ruang Publik
Kisah Mia adalah bukti nyata bagaimana seni bisa menjadi alat bertahan hidup. Trauma yang ia alami datang dari segala penjuru cinta yang dikhianati, beban menjadi ibu tunggal, dan puncaknya, kekerasan negara. Ketika ia tak bisa lagi melukis di penjara, ia mengambil benang dan kain untuk menyulam. Sebuah tindakan yang mungkin dianggap remeh, tapi bagi saya itu adalah strategi bertahan yang luar biasa. Menyulam adalah kerja yang lambat dan butuh fokus. Di tengah kekacauan kamp tahanan, tindakan repetitif menusukkan jarum ke kain bisa menjadi semacam meditasi, cara untuk merebut kembali kendali atas pikiran dan waktu. Di saat tubuhnya dikurung, menyulam adalah satu-satunya ruang di mana ia masih punya kendali.
Menulis memoar di usia senja juga bukan sekadar bernostalgia. Itu adalah terapi. Trauma membuat ingatan kita berantakan. Dengan menuliskannya, ia sedang merapikan kembali kepingan-kepingan hidupnya yang hancur. Mungkin karena itu, pameran ini terasa seperti sebuah ruang terapi bersama. Bukan seperti terapi di ruang dokter, tapi lebih seperti pengakuan kolektif di ruang publik. Luka sejarah ini nyata, dan di ruangan itu, kita semua diizinkan untuk merasakannya bersama. Saat membaca kutipannya di dinding merah, batas antara cerita bangsa dan perasaan saya sendiri jadi kabur. Saya melihat orang lain di sekitar saya juga terdiam, membaca dengan saksama. Ada semacam kesadaran hening di antara kami, bahwa kami sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pameran seni. Kami sedang berpartisipasi dalam sebuah ritual mengingat.
Lalu, Saya Harus Apa?
Pertanyaan ini yang paling mengganggu setelah saya keluar dari pameran. Apa tanggung jawab saya sekarang? Pameran ini menyadarkan saya bahwa seni, di tengah penindasan, bukanlah kemewahan. Meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kehidupan normal terasa seperti sebuah pengkhianatan kecil. Saya merasa punya utang untuk tidak ikut-ikut an lupa. Kalau saya diminta merespons pameran ini, entah kenapa yang terbayang bukanlah lukisan. Tapi kain. Saya membayangkan sebuah instalasi, mungkin saya akan menamainya “Selimut Ingatan”. Selembar kain putih raksasa yang digantung. Di atasnya, saya akan menyulam cerita-cerita perempuan lain yang nasibnya serupa dengan Mia, menggunakan benang merah. Bukan hanya kutipan, tapi mungkin nama, tanggal hilang, atau sepotong kenangan dari keluarga yang ditinggalkan. Pengunjung bisa berjalan mengitarinya, membaca setiap cerita, dan merasakan bagaimana suara-suara yang tadinya berserakan kini ditenun menjadi satu kesaksian yang utuh. Sebuah selimut untuk menghangatkan ingatan kolektif kita, untuk melindungi kerapuhan cerita-cerita ini dari dinginnya ketidakpedulian.
Pada akhirnya, pameran ini membuktikan bahwa kekuatan sebuah cerita tidak terletak pada kemegahannya, tapi pada apa yang berhasil selamat dari upaya penghancuran. Warisannya adalah sebuah metode perlawanan, bahwa di hadapan kehancuran, tindakan merawat dan mencatat ingatan adalah tindakan seni yang paling politis. Mia telah pulang dan ia mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting, jangan pernah menyerah pada gelap. Pameran ini bukan akhir dari sebuah cerita, tapi sebuah awal. Sebuah pertanyaan yang dilemparkan kepada kita semua: mau diapakan ingatan ini sekarang? Mia Bustam meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekadar lukisan yang hilang, ia mewariskan sebuah metode perlawanan bahwa saat berhadapan dengan kehancuran, tindakan merawat, mencatat, dan menyulam ingatan adalah tindakan artistik sekaligus politis yang paling kuat. Ia telah pulang ke Yogyakarta, bukan hanya sebagai seniman, tetapi sebagai guru yang mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada kegelapan sejarah. Pameran ini adalah sebuah panggilan, sebuah pengingat bahwa perjuangan melawan kelupaan adalah tugas yang tak pernah selesai, dan seni adalah salah satu senjata kita yang paling ampuh.
Daftar Acuan
Benjamin, W. (1968). The work of art in the age of mechanical reproduction. Dalam Illuminations, disunting oleh Hannah Arendt. Schocken Books.
Marcuse, H. (1978). The aesthetic dimension: Toward acritique of Marxist aesthetics. Macmillan Education.
Tim Riset Penelitian dan Pameran “Mia Bustam”. (2025). Mia Bustam. Tim Riset Penelitian dan Pameran “Mia Bustam”.
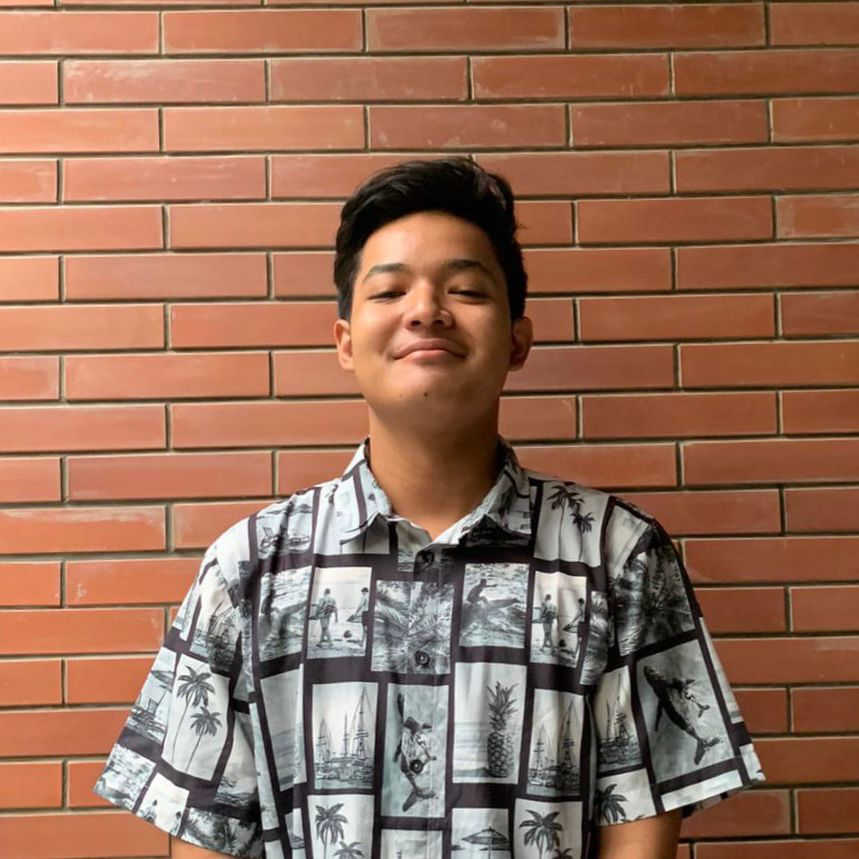
Dominikus Bondan Pradipta adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Program Sarjana Universitas Sanata Dharma (PSPPS-USD). Ia suka berpetualang dan menikmati suasana alam.



