Dalam salah satu buku yang cukup populer, The Construction of Personality (1982; kemudian dicetak ulang 1986), Hampson (1986) menuliskan bahwa pendekatan konstruktivis melihat kepribadian sebagai proses yang melewati rangkaian tahap perkembangan dan senantiasa terjadi dalam rentang hidup serta sangat mungkin berubah tergantung situasi dan pengalaman hidup. Baik Jean Piaget atau Erik Erikson merupakan tokoh psikologi dengan pendekatan konstruktivis. Menurut Piaget, terdapat empat tahap perkembangan kognitif dari bayi hingga remaja menjelang dewasa, yakni sensorimotor, pra-operasional, operasional konkrit, dan operasional formal (Ginsburg & Opper, 1969). Sementara Erikson (1959/1980) menunjukkan bahwa ada delapan tahap perkembangan psikososial, yakni dari tahap pertama yang ditulis Erikson sebagai Trust vs Mistrust (kepercayaan vs ketidakpercayaan, usia 0-18 bulan) hingga tahap kedelapan Integrity vs Despair (integritas vs keputusasaan, usia kurang lebih 65 tahun).
Mengapa keduanya disebut sebagai konstruktivis dan bukan konstruksionis? Apa yang membedakan kedua istilah tersebut? Dalam perdebatan akademis, seringkali kedua istilah tersebut digunakan secara serampangan dan abai pada perbedaan epistemologis keduanya. Secara epistemologis, persamaan keduanya adalah bahwa pengetahuan dan fenomena psikologi tersusun sesuai dengan rentang hidup individu dalam konteks hidup tertentu dan bahwa pengetahuan dan realitas memiliki sisi subyektif (relativistik). Perbedaan mendasarnya, para konstruktivis meyakini bahwa pengetahuan dan realitas dikembangkan dalam diri individu, yakni lewat proses biologis dan kognitif (biological and cognitive processes). Sementara itu, konstruksionis meyakini bahwa pengetahuan dan realitas berada dan dikonstruksi lewat wacana dan percakapan atau dengan kata lain lewat pertukaran sosial (social interchange). Pentingnya wacana dan percakapan dalam pertukaran sosial ini kemudian berimplikasi pada ketiadaan fenomena psikologis tanpa hadirnya bahasa. Bahasa menjadi perkara penting yang menentukan cara pandang dan penciptaan makna seseorang.
Dalam disiplin Psikologi, gagasan terkait ‘kepribadian’ menjadi contoh yang baik untuk memahami konstruksionisme sosial. Kepribadian menjadi pusat untuk memahami siapa diri kita dan siapa orang lain — dengan kata lain, kepribadian mempertanyakan apa artinya menjadi seseorang. Konstruksionisme sosial justru mempertanyakan: Apakah kita ini memiliki kepribadian? Apakah emosi kita ini dihasilkan dari sesuatu yang kita sebut sebagai kepribadian? Dengan berpijak pada pemikiran Vivien Burr, tulisan ini mencoba untuk menantang pandangan umum mengenai kepribadian.
Kepribadian dalam Cara Pandang Tradisional
Istilah ‘kepribadian’ umumnya mengacu pada karakteristik yang relatif stabil dari perasaan, pemikiran, dan tindakan individu (Sloan, 2014). Definisi kepribadian bervariasi sesuai dengan perspektif teoritis dari mana kepribadian dipandang (Burr, 1995). Sebagai contoh, psikologi humanistik memandang kepribadian sebagai lokus keunikan, pertumbuhan, dan integrasi individu. Pendekatan behavioris mendefinisikan kepribadian sebagai konsekuensi dari penguatan sebelumnya dan rangsangan situasional saat ini. Teori psikoanalitik melihat kepribadian sebagai ekspresi dari hubungan interpersonal yang sebelumnya diinternalisasi dan berbagai kompromi yang tidak disadari yang dibangun dalam proses mengelola dorongan, keinginan, dan larangan. Kesamaan yang dimiliki sebagian besar pendekatan adalah bahwa mereka memperlakukan kepribadian sebagai sintesis dari kognisi, emosi, motivasi, temperamen, dan banyak aspek lain dari fungsi psikologis. Kepribadian adalah konsep global seperti diri atau jiwa.
Dari pendefinisian kepribadian tersebut, dapat dipahami bahwa kepribadian dilihat sebagai sesuatu yang secara individual unik dan relatif stabil (Hampson, 1988; Burr, 1995). Stabil dalam hal ini diartikan bahwa kecenderungan kepribadian untuk berubah amatlah kecil. Perubahan kepribadian dipandang sebagai sesuatu yang hanya terjadi sebagai hasil dari beberapa peristiwa besar dalam kehidupan (misalnya: ‘Wahyu menjadi jauh lebih tidak bertanggung jawab sejak ayahnya meninggal’) atau sebagai hasil dari beberapa intervensi yang direncanakan, seperti pergi ke terapis untuk meminta bantuan dalam menyingkirkan rasa malu yang berlebihan.
Selain dianggap unik dan relatif stabil, kepribadian juga mesti koheren — tidak kontradiktif satu sama lain (Hampson, 1988; Burr, 1995). Jika saya menjelaskan kepada Anda seseorang yang baru saja saya temui, dan memberitahu Anda bahwa mereka mandiri, berpikiran luas, gegabah, suka bersenang-senang, tumpul pikirnya, dan suka berteman; Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam menyusun gambaran mental tentang orang tersebut. Tetapi jika saya mengatakan bahwa orang ini ramah, gugup, kompeten, tidak berpikir panjang, dan hangat, Anda mungkin akan mengalami kesulitan untuk membayangkan gambaran mental orang tersebut. Kita mengandaikan bahwa kepribadian seseorang bersifat konsisten, terdiri dari serangkaian karakteristik yang memiliki kemiripan. ‘Menyenangkan’, ‘terburu-buru’ dan ‘suka berteman’ tampak bisa dirangkai dengan ‘tidak kompeten’, ‘sembrono’ dan tidak ‘hangat’. Apa yang kita lihat dalam diri kita dan orang lain adalah kepribadian yang menyatu, diri yang koheren dan konsisten.
Selain ketiga aspek kepribadian ini — perbedaan individual (unik), stabilitas, dan koherensi — juga ada aspek penting keempat; yakni bahwa kepribadian menentukan perilaku kita (Hampson, 1988; Burr, 1995; Sloan, 2014). Apa yang kita lakukan merupakan cerminan dari kepribadian kita. Seseorang memukul temannya karena ia seorang yang agresif. Namun, bagaimana jika ternyata kepribadian merupakan hasil dari perilaku kita? Dengan kata lain, justru orang dikatakan agresif karena orang lain melihat bahwa orang tersebut melakukan tindak agresi.
Empat aspek kepribadian berupa keunikan, stabil, koheren, dan bahwa sifat tersebut menentukan perilaku merupakan bentuk esensialisme. Kita menganggap ada ciri mutlak dari diri kita. ‘Esensialisme’ adalah cara memahami dunia yang melihat benda-benda (termasuk manusia) memiliki esensi atau sifat mereka sendiri, sesuatu yang dapat dikatakan milik mereka dan yang menjelaskan bagaimana mereka berperilaku. Kiguwa (2014) menuliskan bahwa esensialisme merupakan gagasan yang mengakui bahwa identitas bersifat menetap dan tidak berubah, atau fakta fisik dan sosial (gender, kelas, ras) menentukan siapa diri dan identitas kita. Benda seperti kursi, kertas, plastik, atau sendok tidak ‘berperilaku’ dalam pengertian manusia ‘melakukan sesuatu’, tetapi mereka bereaksi secara berbeda terhadap kondisi lingkungan yang berbeda, dan reaksi ini dapat dijelaskan dalam hal yang kita ketahui tentang ‘sifat’ dari plastik atau kayu. Berbeda dengan meja plastik, meja kayu tidak akan ‘mleyot’ apabila kita menumpuk buku di atasnya. Dengan cara yang sama, kita berpikir bahwa orang yang pemalu tidak cocok dipekerjakan sebagai humas.
Masalah yang Muncul dalam Cara Pandang Tradisional
Terkait pemahaman dan pendefinisian kepribadian dalam cara pandang tradisional di atas, muncul beberapa masalah (Hampson, 1988; Burr, 1995). Masalah pertama adalah gagasan bahwa “personality really exists”. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda memiliki ‘kepribadian’? Jika saya meminta bukti kepada Anda bahwa, katakanlah, Anda memiliki mata cokelat, atau bahwa Anda tinggal di rumah adat, masalah itu akan diselesaikan dengan sangat cepat. Anda bisa membiarkan saya melihat mata Anda dan Anda bisa menunjukkan rumah Anda. Namun, bisakah Anda menunjukkan kepribadian Anda kepada saya? Di mana hal tersebut terletak? Bahkan jika seorang ahli bedah melakukan operasi bedah dalam diri kita, dia tidak akan menemukannya. Tidak ada bukti obyektif yang dapat Anda berikan untuk menunjukkan keberadaan kepribadian Anda. Namun, kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang mendaku kepribadian sebagai kambing hitam yang mesti bertanggungjawab atas sikap dan hal-hal yang kita lakukan.
Persoalan lain terkait “personality really exists” adalah kita seperti diharuskan untuk menemukan kepribadian kita (Burr, 1995). Toh, tidak semua masyarakat mengakui adanya kepribadian. Beberapa masyarakat mengakui bahwa apa yang orang-orangnya lakukan disebabkan karena adanya jiwa-jiwa yang tidak kelihatan (invisible spirits and demons). Ketika individu dalam masyarakat ini kemudian diminta menemukan kepribadiannya, maka gagasan soal kepribadian tidak akan muncul dalam skema mereka. Bahkan, boleh jadi masyarakat ini kemudian dianggap gila oleh mereka atau masyarakat lain yang memiliki konsep “kepribadian”. Masalah ini barangkali disebabkan oleh karena adanya pendidikan dan pemahaman soal kepribadian. Namun penekanannya adalah pada klaim terhadap pemegang kebenaran, kita (yang mengenal konsep ‘kepribadian’) merasa diri kitalah yang lebih benar dan pemikiran masyarakat tersebut salah. Ketika menempatkan diri sebagai pemegang kebenaran, maka potensi untuk melakukan opresi dan penyalahan — terhadap masyarakat yang memiliki cara konstruksi kebenaran yang berbeda — akan terbuka lebar (Kiguwa, 2014).
Sebagai contoh kekeliruan pemahaman bahwa “personality really exists” adalah analisis Erich Fromm (1961/2004/2005) terkait struktur masyarakat kapitalis. Bagi Fromm (sekalipun dia bukan seorang social constructionist), apa yang dinamakan “human nature” adalah produk dari struktur masyarakat dan ekonominya. Ia mengatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis, kata kuncinya adalah kompetisi. Struktur masyarakat yang dibentuk oleh sifat kompetisi ini kemudian menciptakan orang yang kompetitif dan dengan demikian menciptakan model orang berdasarkan perbedaan individual. Dengan kata lain, Fromm berpendapat bahwa sifat kompetitif, pribadi yang serakah, atau produktif merupakan hasil dari struktur sosial ekonomi — alih-alih sifat dasar manusia.
Masalah kedua adalah adanya kecenderungan psikologisasi (psychologisation) atau menggunakan kata-kata untuk menggambarkan peristiwa internal seperti perasaan, dan bukan perbuatan (Burr, 1995; Álvarez-Uría, Varela, Gordo & Parra, 2010; Kesel, 2010). Sebagai contoh, ketika orang membicarakan ‘cinta’, akan ditemukan dua tema khusus: cinta sebagai bentuk tindakan dan cinta sebagai bentuk perasaan. Cinta sebagai bentuk perasaan mendominasi kehidupan sehari-hari kontemporer. Sebagai contoh: ‘Aku memukulnya ketika aku marah — tapi sesungguhnya aku mencintainya’. Kita cenderung lebih menggambarkan kehidupan manusia dalam istilah psikologis daripada apa yang kita lakukan terhadap seseorang. Orang tua yang memukuli anaknya sampai si anak babak belur, mungkin dengan mudah mengatakan bahwa itulah cara dia mencintai dan merawat anaknya.Penyebaran wacana psikologi melampaui batasan disiplin ilmu ini seringkali memunculkan masalah dengan penyelesaian secara psikologis untuk kasus apapun (Voz, 2014). Ketika Anda membutuhkan kepastian jaminan kesehatan selama pandemi, Anda justru diberi seminar atau himbauan cara berbahagia atau tidak tertekan selama pandemi berlangsung.
Masalah ketiga adalah, menurut Burr (1995), betulkah kepribadian bersifat relatif stabil? Apabila memang demikian, cobalah amati apa yang Anda lakukan; apakah Anda berperilaku sama ketika berada di dalam kelas dan di kantin kampus? Apakah cara Anda berbicara dengan petugas sekretariat sama dengan cara Anda berbicara dengan kawan akrab Anda? Apabila tidak; maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa: cara kita berperilaku, berpikir, dan merasa akan sangat berbeda tergantung dengan siapa, apa yang kita lakukan, dan mengapa kita melakukannya (Burr, 1995; Burr, 1998). Dalam teori belajar sosial, kita akan mempelajari bahwa situasi spesifik tertentu yang akan menentukan cara kita berperilaku. Sementara itu, dalam Sosiologi kita akan menemukan gagasan ‘peran’ yang menentukan kita berperilaku. Miisal seorang ibu yang sekaligus adalah seorang dekan atau seorang karyawan sebuah perusahaan akan dilihat berbeda berdasarkan konteksnya. Ketika ibu tersebut berada di rumah, ia dievaluasi berdasarkan pembagian tugas keluarga, tetapi ketika di tempat kerja, evaluasi akan diarahkan pada bagaimana ia menunaikan tugas kantornya. Sekalipun kedua teori tersebut bukanlah contoh KS, tetapi keduanya memperlihatkan pada kita bahwa ada arena terbuka untuk alternatif penjelasan dan kita bisa memperselisihkan konsep ‘kepribadian’.
Masalah keempat terkait erat dengan masalah ketiga; sekali kita memandang bahwa ‘kepribadian’ bersifat stabil, maka kita menafsirkan bahwa kita memiliki kepribadian yang koheren dan konsisten satu sama lain (Burr, 1995). Psikoanalisis menunjukkan bahwa konflik dan inkonsistensi terjadi karena kita memiliki alam ketidaksadaran. Dalam teori peran dikatakan bahwa terdapat ‘konflik peran’, misalnya: saya ayah sekaligus guru dari anak ini, bagaimana saya berinteraksi dengannya di rumah? Atau dalam materialisme dialektik dikatakan bahwa fenomena mungkin terjadi karena adanya kontradiksi dalam kondisi material. Masalah keempat ini menunjukkan bahwa konflik dan inkonsistensi adalah kenyataan sehari-hari kehidupan kita (Burr, 1998; Hampson, 1986).
Konstruksi Sosial Kepribadian
Apa artinya mengatakan bahwa kepribadian dikonstruksi secara sosial? Taruhlah Anda memiliki seorang kawan, kemudian deskripsikan tipe kepribadiannya. Anda menyebutkan bahwa ia ramah, peduli, mawas-diri, menarik, atau moody. Dapatkah Anda menyebutkan tipe kepribadian tersebut tanpa merujuk pada bagaimana ia berperilaku dengan Anda atau dengan orang lain? Tanpa kehadiran orang lain, apakah ia bisa menjadi orang yang ramah atau peduli? Poinnya adalah; seolah-olah kita menggunakan tipe kepribadian seseorang dengan merujuk pada gagasan bahwa entitas tersebut ada di dalam diri orang termaksud; tetapi sekali orang tersebut disingkirkan dari relasinya dengan orang lain maka kata-kata yang disebutkan menjadi tak berarti (Burr, 1995; Burr, 1998).
Selanjutnya, pikirkan seseorang yang Anda kenal akrab. Bayangkan bagaimana keadaan Anda saat bersama orang itu. Mungkin Anda merasa bahwa saat bersamanya Anda berkepala dingin dan rasional. Dia tampaknya selalu berkutat dari satu krisis ke krisis lain dan kagum dengan kemampuan Anda untuk menentukan langkah. Sifat hubungan dengan Anda layaknya psikolog dengan klien; atau Anda sebagai yang dianggap “kuat” sementara orang tersebut sebagai yang “lemah”. Sekarang pikirkan orang lain yang berlawanan dengan Anda. Dengan orang ini, Anda sepertinya selalu mencurahkan masalah Anda, meminta nasihat dan mengambil arahan darinya. Dari kedua “Anda” tersebut, mana “Anda” yang sebenarnya? Ya keduanya! Setiap versi dari “Anda” adalah produk dari hubungan Anda dengan orang lain (social interchange). Setiap “Anda” dibangun secara sosial, dari pertemuan sosial yang membentuk hubungan Anda.
Jika kepribadian bergantung pada dengan siapa Anda berhubungan, maka persolan bukan saja pada teori kepribadian tetapi juga merujuk pada bagaimana kita mempersepsikan orang. Salah satu pertanyaan kunci dalam mempersepsikan seseorang adalah: bagaimana kita dapat membuat penilaian akurat tentang kepribadian seseorang? Gagasan akurasi mengasumsikan ada yang “benar” dan “salah” tentang seperti apa seseorang itu sebenarnya. Cobalah pikirkan tiga kata atau istilah (jenis kepribadian) untuk menggambarkan diri Anda. Sekarang pikirkan tiga kata yang mungkin digunakan orang tua Anda untuk menggambarkan Anda. Terakhir, pikirkan tiga kata yang mungkin digunakan pacar atau seorang yang akrab dengan Anda untuk mendeskripsikan pribadi Anda. Setidaknya akan ada beberapa perbedaan antara ketiga deskripsi. Namun siapa yang benar? Jika hanya ada satu Anda yang sebenarnya, satu kepribadian, apakah dengan demikian ada dua deskripsi lain yang salah? Konstruksionisme sosial, berbeda dengan konstruktivisme, mengatakan bahwa setiap versi ‘Anda’ adalah produk dari hubungan Anda dengan orang-orang termaksud, sesuatu yang dibuat dan dibangun di antara kalian (Burr, 1995; Burr, 1998). Bias dan kesalahan dalam mempersepsikan (dan mengatribusikan) seseorang bertumpu pada asumsi mendasar bahwa seseorang memiliki kepribadian tertentu yang mesti ia “temukan” (catatan: orang-orang yang mendalami konstruksionisme sosial lebih sering menggambarkan manusia dengan “identitas”).
Alih-alih melihat kepribadian sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam bentuk sifat atau karakteristik, kita dapat melihat diri kita atau orang lain sebagai produk dari perjumpaan dan hubungan sosial — singkat kata: kepribadian secara sosial dikonstruksi (socially constructed). Bagaimana konstruksi sosial ini berlangsung? Sebagai contoh, kita akan mengamati bagaimana pembentukan kepribadian dalam perbedaan gender terjadi dalam pengalaman sehari-hari.
Gender dan Pembentukan Kepribadian
Burr (1998) menyatakan bahwa psikologi secara khusus mendefinisikan diri sebagai studi terhadap individu-individu. Implikasi dari pernyataan tersebut, psikologi menjadi disiplin yang memiliki keraguan untuk mempertimbangkan konteks sosial seseorang dalam memproduksi perilaku dan pengalaman. Sebagai contoh, melalui pendekatan eksperimen dan psikometri, penelitian seringkali berminat menyajikan dan menganalisis perbedaan antar-jenis kelamin atau seks. Dari hasil penelitian terkait perbedaan kategori seks, penelitian literatur Maccoby dan Jacklin (1974) menemukan bahwa ada empat area yang membuktikan bahwa laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan karakteristik berdasarkan kategori seksnya, yakni (1) seiring berjalannya waktu, perempuan memiliki kompetensi kemampuan verbal dibanding laki-laki; (2) laki-laki memiliki kemampuan visual-spasial yang lebih baik dibanding perempuan, (3) kemampuan matematis laki-laki jauh lebih berkembang dibanding perempuan (terkait poin 2); dan (4) sejak masa kanak-kanak, laki-laki cenderung agresif secara verbal maupun fisik dibanding perempuan.
Sekalipun konsistensi perbedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki terjadi dalam keempat area tersebut, mengapa seringkali kita temui bahwa perempuan dan laki-laki dianggap berbeda entah dalam bakat, kemampuan, kapasitas emosional, atau kepribadiannya? Dari mana asal-muasal perbedaan ini muncul? Apakah memang berada dalam tataran genetis-hormonal (nature) atau lingkungan (nurture)? Atau jangan-jangan penelitian terkait perbedaan seks ini justru menunjukkan bahwa kita-lah yang meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda dari sono-nya — alih-alih menunjukkan perbedaan dari keduanya? Sebelum abad ke-18, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki alat genital yang sama, hanya laki-laki berada di luar dan perempuan berada di dalam (Laqueur, 1990), tetapi pengetahuan tersebut kini telah berubah sebagaimana kita pahami hari ini. Artinya, penelitian dan perdebatan tentang bagaimana perubahan tersebut terjadi menjadi perkara penting dalam dunia keilmuan.
Terkait seks, perdebatan dalam dunia akademik seringkali diwarnai dengan menekankan pentingnya faktor biologis sebagai determinan fenomena psikologis (Burr, 1998; Riley & Evans, 2017). Argumen dari faktor biologis tersebut tampil dalam berbagai penelitian yang menekankan bahwa dorongan biologis (biological drive) menjadi determinan perilaku alkoholik, gangguan mental, kriminalitas, homoseksualitas, atau perbedaan gender. Sekalipun pengaruh lingkungan tetap dimasukkan dalam analisis, tetapi posisinya jauh lebih lemah dibanding faktor biologis. Lingkungan hanya sekadar menjadi moderating effect atau variabel yang memungkinkan terjadinya pengaruh antara dua variabel lain tetapi tidak menjadi variabel pokok yang menentukan pengaruh. Atau, dalam kasus lain, lingkungan dilihat sebagai faktor yang membuat perkembangan individu menjadi tidak optimal.
Cara pandang biologis tersebut kemudian berkembang ke gagasan sosio-biologis yang menunjukkan bahwa laki-laki secara genetis diprogram lebih agresif dan perempuan bersifat memelihara atau merawat (Burr, 1998). Gagasan sosio-biologis ini berasal dari jaman berburu dan meramu yang kemudian membagi peran gender ke dalam dua area, laki-laki bertugas untuk mencari makanan atau berburu dan perempuan menjaga rumah dan merawat anak. Pembagian tersebut didasarkan pada perempuan akan mengandung anak dan karenanya perhatian perempuan mesti diarahkan ke anak, dengan demikian berburu merupakan pekerjaan yang tidak sesuai untuk si perempuan. Apa yang terjadi kemudian adalah determinisme seks yang membagi peran gender berdasarkan peran sosial dan biologis antar-seks.
Apabila kepribadian seseorang berbeda dan ditentukan oleh peran gendernya serta predisposisi biologisnya, kita akan menemukan bahwa dalam setiap masyarakat di dunia pola tersebut pasti terjadi. Studi lintas budaya justru menunjukkan hasil sebaliknya. Dalam studi lintas budaya, sosialisasi menjadi proses penting dalam menentukan peran dan perbedaan gender. Beberapa masyarakat non-Barat menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian masyarakat seperti merawat, giat, atau mandiri melekat baik pada perempuan maupun laki-laki (Burr, 1998). Dengan demikian, bukan lagi soal predisposisi biologis, perhatian terhadap sosialisasi individu pada masa hidupnya menjadi perkara penting untuk diperhatikan. Pilcher dan Whelehan (2004) mengatakan bahwa sosialisasi memungkinkan individu belajar menjadi maskulin atau feminin dalam perkara identitas, perilaku, penampilan, atau nilai-nilai. Dengan kata lain, kita diajari untuk mengapropriasi ciri-ciri kedirian atau kepribadian yang sesuai dengan jenis kelamin kita.
Bagaimana apropriasi tersebut berlangsung? Burr (1998) mengatakan bahwa teori yang menjelaskan bagaimana sosialisasi terjadi adalah social learning theory (SLT). SLT menekankan pada proses imitasi, modeling, dan belajar dari model. Gagasan yang bermula dari pemikiran Albert Bandura ini kira-kira berargumen bahwa seseorang mengobservasi perilaku yang dianggap wajar berdasarkan gender lalu diapropriasi oleh lingkungannya. Karena melihat bahwa apropriasi perilaku atau sifat tertentu memperoleh apresiasi, maka si anak kemudian mempraktikkannya.
Pada praktiknya, SLT memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kekuatan dan resistensi dalam identitas gender (Burr, 1998). Selanjutnya, munculah teori mengenai peran pengalaman hidup dalam memahami kepribadian dalam ranah identitas gender. Ranah dalam hal ini dibagi ke dalam dua arena, publik dan privat. Peran perempuan lebih dominan dalam menentukan kehidupan privat rumah tangga. Mereka harus memastikan anak dan keluarga bahagia dan sehat. Mereka dibebani tanggung jawab untuk mengurus perselisihan yang terjadi antar-anak atau keluarga. Sementara itu, peran laki-laki berada dalam ranah publik yang mana menempati peran, tugas, dan tanggung jawab untuk berhadapan dengan dunia luar yang lebih minim tanggung jawab dalam merawat — sebab berhubungan dengan orang di luar keluarga yang menjadi rekan kerja. Moralitas yang terbentuk dalam sistem demikian adalah: perempuan mengedepankan isu kepedulian dan tanggung jawab, sementara laki-laki lebih pada hak dan kewajiban. Dari sinilah kemudian muncul gagasan mengenai peran gender yang diterima dan dipraktikkan sebagai aturan tak tertulis (unwritten rules).
Selain SLT, pengalaman hidup, atau peran gender; dalam pemahaman mengenai perbedaan seks berbasis kerangka sosialisasi kemudian muncul kategori feminis liberal dan radikal (Burr, 1998). Gagasan yang seringkali digunakan feminis liberal kira-kira mengedepankan tumbuhnya kesadaran dalam merawat anak, pemerolehan pendidikan, dan perubahan sikap terhadap peran gender. Selain itu, muncul pula pandangan dari feminis radikal yang melihat perbedaan gender dalam norma heteroseksual sebagai bentuk dominasi laki-laki dan penundukan terhadap perempuan (terjadi opresi terhadap perempuan) dalam ranah publik maupun privat. Sebagai contoh adalah kasus perkosaan atau pelecehan seksual. Perkosaan dianggap sebagai proses yang secara sadar mengintimidasi perempuan dan menempatkannya pada kondisi takut. Ancaman terhadap perkosaan ini kemudian memungkinkan perempuan tetap berada dalam ranah domestik dan di bawah perlindungan seorang lelaki lewat sebuah pernikahan. Apa implikasi terhadap kedirian atau kepribadian perempuan? Implikasi lebih jauh adalah terjadi reproduksi pandangan umum bahwa perempuan memang pantas dalam ranah domestik, dalam ranah tersebut seorang perempuan perlu menjadi pribadi yang merawat, peduli, lemah-lembut, penurut, pemalu, peka terhadap orang lain, dan tentu saja lebih tidak berani dibanding laki-laki yang digambarkan mampu melindunginya.
Melihat bagaimana pendefinisian dan identifikasi karakteristik dalam perbedaan seks dari waktu ke waktu, dengan demikian, apakah konstruksi kepribadian (atau lebih pas “identitas” tersebut mungkin berubah? Apakah kepribadian, dalam pemahaman bahwa hal tersebut konsisten, memang eksis? Kalaupun eksis, apakah kepribadian menjadi satu-satunya penentu perilaku seseorang? Bukankah, bahkan secara akal sehat saja, cara kita berperilaku juga ditentukan siapa diri dan situasi yang tengah kita hadapi?
Daftar Acuan
Álvarez-Uría, F., Varela, J., Gordo, Á & Parra. (2010). Psychologised life and thought styles. Annual Review of Critical Psychology, 8, hlm. 11-27.
Burr, V. (1995). An introduction to social constructionism. London & New York: Routledge.
Burr, V. (1998). Gender and social psychology. London & New York: Routledge.
Erikson, E.H. (1959/1980). Identity and the life cycle. New York & London: W.W. Norton & Company.
Fromm, E. (2005). Marx’s concept of man. London & New York: Continuum.
Ginsburg, H. & Opper, S. (1969). Piaget’s theory of intellectual development: An introduction. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Hampson, S. (1986). The construction of personality. London & New York.
Kesel, M.D. The rational(e) of an emotional society: A cartesian reflection. Annual Review of Critical Psychology, 8,hlm. 123-132.
Kiguwa, P. (2014). Feminist critical psychology in South Africa. Dalam D. Hook (Ed.), Introduction to critical psychology (hlm. 279-315). Claremont: UCT Press.
Laqueur, T. (1990). Making sex: Body and gender from the Greeks to Freud. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Maccoby, E. and Jacklin, C. (1975) The psychology of sex differences. Stanford, CA: Stanford University Press.
Pilcher, J. & Whelehan, I. (2004). Fifty key concepts of gender studies. London, Thousand Oaks & New Delhi: SAGE Publications.
Riley, S. & Evans, A. (2017). Gender. Dalam B. Gough, The Palgrave handbook of critical social psychology. London: Palgrave Macmillan.
Sloan, T. (2014). Personality. Dalam T. Teo, Encyclopedia of critical psychology (hlm. 1364-1368). New York: Springer-Verlag.
Voz, J.D. (2014). Psychologization. Dalam T. Teo, Encyclopedia of critical psychology (hlm. 1547-1551). New York: Springer-Verlag.

Editor Nalarasa pada rubrik Teori. Sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.



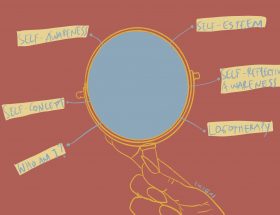
Dari pernyataan ini “kepribadian bergantung pada dengan siapa Anda berhubungan” saya ingin bertanya mas, berarti apakah alat test untuk mengukur kepribadian itu validitasnya harus di pertanyakan ?? seperti test TAT yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian, yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam apersepsi terhadap lingkungan. Jika menyangkut pernyataan tersebut, apakah hasil dari test TAT tersebut akan selalu berubah-ubah bergantung pada hubungan interpersonalnya ??