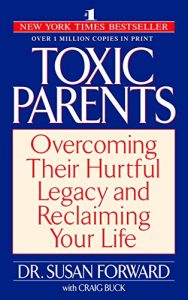
Susan Forward & Craig Buck. (1989/2002). Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life. Bantam Books. 320 hlm.
Keluarga adalah ruang permulaan belajar bagi seseorang. Bagi sebagian besar manusia, hal sederhana seperti makan, menggunakan toilet, mengancing baju, hingga ke hal-hal yang lebih rumit dipelajari lewat keluarga. Keluarga menjadi arena pembentukan kedirian si anak. Pentingnya keluarga tercermin dari peran para anggotanya, terutama orang tua. Tidak sedikit orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar kelak si anak dapat sukses. Ada sebuah ungkapan, bahwa tidak mungkin orang tua ingin memberikan sesuatu yang buruk bagi anaknya. Lazim kita dengar bahwa setiap orang tua menghendaki anaknya lebih sukses daripada dirinya.
Proses menjadi sukses menempuh berbagai dinamika. Anak diajarkan disiplin dan mengikuti aturan sejak dini. Anak mengenal punishment (hukuman) sejak masih balita. Seringkali anak mendapatkan sebuah hukuman, bukan karena kesalahannya semata. Dengan memosisikan anak sebagai yang paling lemah dalam keluarga, orang tua kerap melakukan displacement kepada anak. Sang anak pun menginternalisasi bahwa hal tersebut memang akibat kesalahan atau ketidakmampuan dirinya. Ada ungkapan bahwa orang tua tidak dapat memilih memiliki anak macam apa. Namun, harus diingat pula bahwa anak tidak pernah memilih untuk hadir di dunia. Meminjam bahasa eksistensialisme, si anak terlempar ke dunia. Anak juga bukan individu yang sempurna, bahkan lebih-lebih mereka (dianggap) masih berada dalam tahap belajar.
Persoalan keluarga dan anak memunculkan istilah yang kini populer disebut toxic family. Toxic family, dysfunctional family atau keluarga disfungsional seolah tak pernah diakui kehadirannya. Hal ini bertentangan dengan norma dan agama yang mengatakan bahwa keluarga adalah arena yang penuh dengan keharmonisan. Bahkan, dalam agama tertentu jelas-jelas ada aturan untuk menghargai orang tua dan menjadi sebuah dosa besar apabila anak melanggarnya. Pemahaman bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di dunia, semakin menguatkan posisi orang tua bahwa mereka berkuasa dalam hidup seorang anak. Menjadi sangat tidak mungkin untuk menentang orang tua bahkan meninggalkannya. Pepatah “surga ada di bawah telapak kaki ibu” menuntut anak untuk selalu menghargai ibunya tanpa pengecualian. Hal-hal tersebut seringkali dijadikan dalih dan menjadikan orang tua seolah-olah kebal terhadap kritik. Betul memang tidak ada sekolah yang mengajarkan bagaimana cara menjadi orang tua, kebanyakan orang tua mengadaptasi bagaimana dulu ia dibesarkan oleh orangtuanya.
Pemasalahan dalam keluarga disfungsional tidak hanya sebatas kekerasan fisik, tetapi juga sesuatu yang menghambat perkembangan psikis dan emosi anak. Pola yang anak peroleh dalam keluarga disfungsional seringkali membuat si anak menyalahkan diri seumur hidupnya, padahal mungkin itu bukan murni kesalahannya. Ketika dewasa, si anak berpotensi mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau terhubung dengan dirinya dikarenakan masa lalunya. Tidak dapat dipungkiri, sejarah memang hal yang penting bagi manusia, baik itu sejarah sosial maupun sejarah individual. Persoalannya, kebanyakan anak yang dibesarkan oleh keluarga disfungsional tidak menyadari permasalahan yang disebabkan oleh masa lalunya.
Dalam buku Toxic Parents (1989), Susan Forward menceritakan kisah kliennya berhadapan dengan keluarga disfungsional. Susan menjelaskan dinamika seorang anak yang memiliki orangtua toxic dengan sederhana. Rasanya seperti membaca buku harian yang ditambah dengan bumbu-bumbu ilmiah. Bumbu-bumbu tersebut dirasa pas, tidak berlebihan. Saya membandingkan buku serupa yakni The Boy Who Was Raised as a Dog karya Bruce Perry, yang adalah seorang neurologist. Kedua buku ini sama-sama menceritakan mengenai orang-orang yang mengalami persoalan keluarga. Memang keduanya memiliki subyek yang berbeda, Susan menceritakan anak-anak dewasa bercerita bahwa semasa kecil mereka hidup dalam keluarga disfungsional; sedangkan Perry menceritakan anak-anak yang mengalami hal-hal traumatis dalam hidupnya. Kedua buku ini sama-sama dekat dengan realita, kasus-kasus yang diangkat merupakan kasus yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Susan — bersama Craig Buck — berhasil menyampaikan hal-hal tersebut dengan sesederhana mungkin. Berbeda dengan buku Perry, Susan seolah menulis buku dengan bahasa dan alur pikir yang ramah bagi siapapun, tanpa harus mengerti psikologi atau mengenyam pendidikan psikologi.
Buku Susan Forward terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menceritakan bagaimana ia menemukan pola-pola individu dewasa yang dibesarkan oleh keluarga disfungsional. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dengan hukuman (kekerasan) fisik (corporal punishment) akan cenderung memiliki kesulitan untuk mengungkapkan emosi marah. Tidak hanya itu, Susan dapat merombak pemikiran para pembacanya mengenai gambaran orang tua. Selama ini pandangan dominan sering menggarisbawahi orang tua yang menjadi pelaku aktif dalam melakukan kekerasan terhadap anaknya. Padahal orang tua (biasanya) terdiri dari sepasang manusia dan kejelasan peran tiap orang dalam pasangan tersebut tampaknya luput dari penjelasan detil. Peran seorang yang lain dapat menjadi pelaku aktif maupun pasif. Pelaku pasif adalah orang tua yang tidak melakukan apapun untuk melindungi anaknya ketika pola kekerasan terjadi. Ia seolah-olah “mengizinkan” si pelaku aktif untuk melakukan kekerasan karena merasa tidak berdaya. Secara tidak langsung, orang tua jenis termaksud mempertahankan status quo dalam keluarga. Susan tidak hanya mengajak kita memaklumi keadaan, tetapi juga berpikir-ulang dan melihat dari perspektif lain. Mereka sebenarnya memiliki power untuk menghentikan pola kekerasan yang terjadi, tetapi seringkali upaya tersebut nihil. Mereka seolah lebih memprioritaskan perasaan tidak berdaya atau status quo dalam keluarga daripada melindungi anaknya. Keadaan normalisasi dan naturalisasi perilaku kekerasan tersebut menjadikan kekerasan ini bersifat menular (contagious) — bahkan antar-generasi.
Dengan jeli, Susan mengkritik tentang tren terapeutik yang awalnya berangkat dari “then” dan berubah menjadi “here and now”. Hal tersebut lebih jauh memengaruhi hal-hal yang berlaku dalam terapi. Misalnya, orang-orang mulai meninggalkan terapi tradisional yang lebih banyak menghabiskan ongkos dan waktu, tetapi dengan hasil yang minim. Terapi yang bersifat short-term memang fokus untuk mengubah perilaku destruktif yang ada pada diri seseorang. Namun, berdasarkan pengalaman Susan hal tersebut tidak cukup untuk mengobati simptom yang ada. Seseorang dirasa harus berhadapan dengan sumber dari simptom tersebut. Terapi seperti ini menurutnya merupakan terapi yang efektif untuk dilakukan. Perilaku destruktif diubah sekaligus seseorang berupaya menerima dan melepaskan diri dari trauma masa lalu yang timbul dari sistem toxic dalam keluarga.
Menurut Susan, memang tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua hanyalah manusia biasa yang dapat berbuat salah, kehilangan kesabaran, dan sebagainya. Penyimpangan orang tua dari gambaran idealnya tidak lantas menjadikan mereka sebagai orang tua yang kejam atautoxic. Orang tua juga manusia yang memiliki masalahnya sendiri. Sebetulnya anak dapat menghadapi kemarahan orang tua selama mereka lebih banyak mendapat lebih banyak cinta dan pengertian. Orang tua toxic adalah orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan pola negatif yang konsisten dan dominan.
Susan menceritakan masing-masing jenis keluarga disfungsional dengan ciamik. Ia membuka dengan bagaimana dirinya menemukan klien yang mengalami masalah dengan keluarganya. Tidak sedikit individu dewasa yang dulunya dibesarkan dalam keluarga difsungsional memiliki masalah kepercayaan diri, regulasi emosi, keberartian diri, dan mengalami kesulitan dalam berelasi. Kemudian Susan melanjutkan dengan penjelasan ringan yang membantu pembaca untuk mengerti dinamika psikologisnya tetapi dengan bahasa yang umum. Contohnya, pada Bab 2, Susan bercerita tentang seorang subyek yang orangtuanya tidak mampu mencukupi kebutuhan psikologis. Orang tua yang terlalu fokus pada permasalahan mereka sendiri pada akhirnya mengkondisikan sang anak harus mengambil peran mengasuh dan mengurus keluarga. Ketika anak mengambil peran tersebut, maka kebutuhan-kebutuhannya tidak lagi dianggap penting untuk dipenuhi dan malah sang anak yang harus melakukan pemenuhan kebutuhan orang tua karena dianggap telah menjadi tugas yang seharusnya dilakukan olehnya. Kebutuhan fisik maupun emosional anak bukan lagi perkara penting, yang apabila tidak diperhatikan maka mudah diduga akan memengaruhi perkembangan keberartian-dirinya. Bahkan, ia akan cenderung mengalami kesulitan mengenali kebutuhan maupun emosi yang dirasakan saat beranjak dewasa.
Hal lain yang menarik adalah dalam Bab 8. Dalam bab termaksud, Susan mencoba menjawab pertanyaan:Mengapa orang tua dapat berperilaku demikian pada anak-anaknya? Menurut Susan, keluarga merupakan sebuah sistem. Keluarga mendasari individu dalam membentuk realita ketika masih anak-anak. Sebagai contoh, saat kita masih kanak-kanak, cara kita berinteraksi dengan orang lain didasarkan pada bagaimana sistem keluarga mengajarkan kita untuk melihat dunia. Seseorang yang dibesarkan dalam keluarga disfungsional membentuk pemikiran bahwa tidak ada orang yang dapat dipercayai, merasa tidak layak untuk mendapat perhatian, atau merasa bahwa dirinya tidak akan pernah berhasil dalam hal apapun. Orang tua berperilaku demikian karena mereka juga memiliki orang tua. Sistem keluarga toxic ini menjadi semacam warisan turun-temurun. Satu generasi menyebabkan generasi selanjutnya rusak yang kemudian diulang lagi ke generasi selanjutnya dan selanjutnya. Sistem ini sebetulnya bukan sesuatu yang dibentuk oleh orang tua, tetapi ini merupakan hasil dari akumulasi perasaan, peraturan, interaksi, dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi sebelumnya.
Dalam bagian kedua, Susan menawarkan praktik healing (penyembuhan) kepada pembaca yang tumbuh dalam keluarga disfungsional. Saya suka dengan pembawaan alur serta pembahasaan dalam buku ini. Sejak bagian Introduction, Susan menjanjikan sensasi macam apa yang akan muncul saat kita membacanya. Ketika membaca buku ini, kita seperti diajak mendengarkan seorang teman. Kabar baiknya, teman tersebut berhasil membuat kita penasaran dengan alurnya. Ia merupakan seorang teman yang pandai bercerita dengan gaya sarkastis yang kental. Dalam buku ini, terselip beberapa kuesioner yang dapat membantu pembacanya untuk mengidentifikasi diri. Meskipun demikian, kuesioner ini tidak bisa kita telan mentah-mentah, toh tiap hubungan juga punya detil dan kekhasan masing-masing.
Salah satu bagian yang menarik dalam proses healing adalah terkait dengan para pecandu. Proses ini tidak disarankan bagi para pecandu narkoba atau alkohol aktif ketika membaca buku ini. Baru diperbolehkan ketika para pecandu dianggap waras dan berdaya dalam rentang minimal 6 bulan. Alasannya, akan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk membahas kembali masa lalu yang tidak mengenakan karena para pecandu dinilai cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini dapat membuat ia kembali menjadi pecandu atau menjadi semakin parah tingkat kecanduannya.
Susan juga mengatakan bahwa individu-individu yang mengalami kekerasan fisik maupun pelecehan seksual tetap membutuhkan dampingan dari profesional, buku ini tidak akan cukup untuk mereka. Hal pertama yang ia tawarkan justru kita tidak harus memaafkan orang tua kita. Iya, kita tidak harus memaafkan orang tua. Hal ini menurut saya menarik karena sangat bertentangan dengan hal-hal yang kita ketahui selama ini. Susan menemukan bahwa dengan memaafkan individu-individu tersebut, keaadan belum tentu menjadi lebih baik. Mereka masih merasa buruk akan diri mereka sendiri. Memaafkan tidak membuat perubahan yang signifikan atau perubahan yang bertahan lebih lama dalam hidup mereka. Memaafkan seolah menjadi bentuk denial yang lain, yaitu “bila saya memaafkan mereka, maka saya dapat menanggap bahwa apa yang terjadi tidak terlalu buruk”. Sebenarnya, yang terpenting bukanlah memaafkan mereka, tetapi membebaskan diri dari kontrol orang tua toxic.
Susan menawarkan cara yang menurut saya sangat-sangat bersimpangan dengan norma yang selama ini kita pegang. Menurut Susan, seorang yang besar dalam keluarga toxic butuh untuk merobohkan semua pola pikir yang telah terbentuk semasa hidupnya. Seorang anak akan meyakini apa yang mereka terima sebagai hal yang benar karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membandingkan dengan dunia luar. Tugas seorang terapis, atau bahkan kita sebagai orang biasa, adalah membangun kemampuan untuk melakukan pembandingan dengan dunia lain yang sama sekali berbeda dengan apa yang biasa kita hidupi.
Buku ini mengajak kita untuk membayangkan seperti apa dampak dari keluarga disfungsional dalam kehidupan nyata, apa yang melatarbelakangi jenis keluarga termaksud, dan bagaimana dinamika psikologisnya. Lebih jauh lagi, melalui buku ini, kita diajak untuk lebih memahami bagaimana dinamika seseorang yang dibesarkan dengan berbagai jenis orangtua yang toxic. Patut disayangkan bahwa tradisi menyalahkan diri karena mengalami kekerasan dalam keluarga (atau kekerasan yang dilakukan orang tua) masih banyak dipelihara. Menurut Susan, situasi tersebut memang membuat seorang anak merasa aman. Misalnya ketika seorang anak dipukul kepalanya, ia akan mengatakan bahwa karena ia nakal maka orangtuanya memukul kepala si anak. Namun, apakah ada pembenaran untuk memukul kepala anak? Mengapa mesti memukulnya? Seberapa efektif hukuman dengan kekerasan fisik ini memperkembangkan anak? Kasus-kasus demikian sebetulnya sangat nyata dan dekat dengan kita, tetapi masih terus berlanjut. Pertanyaannya, hingga kapan hal-hal seperti ini harus diwariskan pada generasi selanjutnya?
Susan menggambarkan situasi rumah keluarga disfungsional sebagai “private holocaust”. Anak-anak tersebut tidak memiliki tempat yang aman untuk bersembunyi, lari, atau mendapat perlindungan dari siapa pun. Dari buku ini, setidaknya kita bisa belajar bahwa sudah layak dan sepantasnya seorang anak mendapat perlindungan. Mereka merupakan kelompok rentan yang dengan mudah mengalami penindasan. Lebih menyedihkan lagi, penindasan mungkin dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Baik orang tua maupun anak bisa jadi tidak mengerti bahwa sistem toxic ini berdampak begitu besar dalam kehidupan masing-masing. Sistem toxic ini berpotensi menjadi luka yang terpaksa dibawa anak seumur hidupnya. Apakah luka adalah hal yang pantas untuk kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Saya kira, tak seorangpun sepakat.

Penyuka anjing dan laut, jadi ya suka anjing laut.



