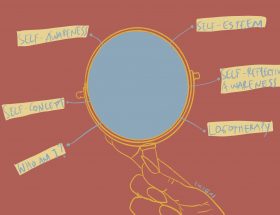Dalam konstruksionisme sosial, bahasa menjadi poin sentral (Burr, 1995; Gergen, 2014). Proses konstruksi berakar pada bahasa. Secara khusus, bahasa mendapatkan peranan penting dalam kajian strukturalisme (berkembang 1900-1960an) dan post-strukturalisme (pasca-1960). Strukturalisme merupakan cara berpikir yang meyakini bahwa perilaku manusia ditentukan oleh struktur masyarakat atau cara berpikir manusia. Kelemahan strukturalisme ini adalah kecenderungan untuk menjadi esensialis atau memahfumi secara fanatik bahwa manusia merupakan produk dari struktur sosialnya. Dengan semangat anti-esensialis atau manusia bukan hanya sekadar produk struktur sosialnya, post-strukturalisme kemudian lahir. Oleh karena itu, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, ada dua hal yang perlu dicatat: sistem (struktur) dan subyek (agensi) (Keucheyan, 2013).
Žižek (2009) menuliskan bahwa apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain adalah kapasitas manusia untuk berbahasa dan dengan demikian merupakan makhluk yang berbicara (speaking being). Karena memiliki bahasa itu pula, manusia dimungkinan untuk melakukan opresi, kekerasan, atau penyingkiran. Dalam berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, pohon jati akan mengeluarkan toksin atau racun yang menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Meskipun secara aktif pohon jati mengeluarkan racun untuk “membunuh” tetapi kita tidak pernah bisa menyebut hal tersebut sebagai kekerasan. Hal tersebut merupakan cara pohon jati “berkomunikasi”. Alelopati (pengeluaran toksin) merupakan interaksi yang sifatnya menetap (fixed) dan tak berubah (stable).
Di lain pihak, bahasa yang dimiliki manusia berpotensi untuk mengalami perubahan makna. Misalnya, istilah “banci” dapat digunakan untuk menggambarkan wadam, tetapi di sisi lain “banci” bisa pula merujuk pada mereka yang berkelamin laki-laki dari bersikap mental pengecut. Lebih jauh lagi, “banci” memiliki perbedaan dengan “homo” atau “gay”. Dalam kajian gender dan seksualitas, Oetomo (1996) menunjukkan bahwa alam pikir orang Indonesia didominasi gagasan bahwa “gay” atau “homo” merujuk pada mereka yang berada dalam kelas menengah ke atas, sementara itu banci dilekatkan pada mereka yang berada dalam kelas menengah ke bawah. Sebab itu, dalam konteks Indonesia, “banci” relatif tidak mengalami perisakan dibanding “gay” atau “homo”. Kalaupun ada perisakan, kasusnya tidak akan separah mereka yang diidentifikasi sebagai “homo” atau “gay”.
Pentingnya bahasa dalam konstruksionisme sosial ini ditunjukkan lewat pendekatan mikro-sosiologis interaksionisme simbolik (Berger & Luckmann, 1966). Gagasan interaksionisme simbolik tersebut mereka kembangkan dari Herbert Blumer, Wilhelm Wundt, dan George Mead. Mead mengembangkan gagasan interaksionisme simbolik yang kira-kira berargumen bahwa orang mengkonstruksi dan menegosiasikan identitasnya lewat interaksi sosial dengan orang lain. Dalam proses konstruksi ini, bahasa menjadi makna simbolik yang dipertukarkan.
Cara Konstruksionisme Sosial Melihat Bahasa
Dalam psikologi tradisional, bahasa dilihat sebagai ekspresi mental dari manusia. Lebih jauh lagi, bahasa merupakan manifestasi ‘asli’ dari gagasan seseorang. Pemahaman ini menutup kemungkinan bahwa manusia bisa berbohong sebab mengenal bahasa — sebab yang mereka katakan kemudian dianggap sebagai fakta yang mencerminkan kehendak dirinya. Kondisi mental seseorang dianggap menjadi preseden terciptanya bahasa atau orang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan sesuatu yang telah ada di dalam konsep mental mereka atau di dunia.
Konstruksionisme sosial, secara khusus post-strukturalisme, melihat bahwa pengalaman atau manusia dikonstruksi lewat bahasa. Karena ada bahasa, maka kedirian orang bisa dikonstruksi. Pemahaman ini hanya bisa kita pahami dalam konteks kekinian di mana bahasa merupakan kapasitas penting yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Bahasa merupakan piranti linguistik yang digunakan manusia untuk melakukan strukturasi pengalaman dan dunianya (Burr, 1995; Burr & Dick, 2017).
Ada dua implikasi dari pemahaman di atas. Pertama adalah ketika kita mengatakan “menjadi manusia”, memiliki kepribadian, memiliki dorongan (drive) dan hasrat, memiliki emosi; berarti memahami bahwa kapasitas tersebut mungkin dimiliki manusia karena hanya lewat bahasa pengalaman dapat distrukturasi. Implikasi kedua adalah bahwa dengan adanya multi-bahasa di dunia ini, maka konstruksi terkait diri atau peristiwa di dunia ini menjadi perkara mendasar dalam konstruksionisme sosial dengan berupaya melihat sebuah fenomena psikologis secara kontekstual.
Berbeda dengan psikoanalisis klasik yang menyatakan bahwa diri kita telah diprogramkan serta memiliki kondisi internal seperti rasa marah, kebencian, atau iri hati; konstruksionisme sosial memandang bahwa konsep-konsep tersebut dipelajari manusia dalam dunianya atau tidak satu hal pun yang terjadi tiba-tiba (nothing is spontaneous, tak terkecuali dengan “hasrat”). Manusia mendefinisikan diri dengan kondisi-kondisi termaksud. Proses belajar lewat bahasa ini bisa menjelaskan mengapa konsep malu (shame atau embarassment) di dunia barat berbeda dengan konsep malu dalam bahasa Indonesia. Malu dalam bahasa Indonesia bisa berarti malu pasif dan malu aktif (Saraswati, 2019). Malu pasif bisa diartikan karena seseorang menjadi pusat perhatian yang berlebihan dari lingkungan sekitarnya. Sementara itu, malu aktif merupakan implikasi dari malu pasif di mana perasaan ketertekanan dalam malu pasif memungkinkan seseorang untuk mengubah diri sesuai dengan norma.
Apakah histeria merupakan luka fisik atau mental? Dalam analisis Breuer dan Freud (1895), perempuan yang mengalami lebam-lebam dikatakan mengalami histeria. Apabila kita membaca lebam-lebam ini sebagai sebuah bahasa — sebagaimana dilakukan Breuer dan Freud — mungkin hal tersebut menunjukkan bahwa yang tampak di kulit merupakan perwujudan dari hasrat yang direpresi. Pertanyaan tersebut mirip dengan ketika kita mengatakan “pusing”, apakah pusing yang dimaksud adalah karena penyebab organik ataukah pusing karena mental atau kesukaran psikologis? Jawaban pertanyaan tersebut tidaklah mudah, hal ini disebabkan kita terbiasa mempelajari bahwa dalam kategori Cartesian, manusia terbagi menjadi dua elemen, yakni fisik dan mental (Manichean dualism). Contoh lain adalah soal homoseksual. Alih-alih dikondisikan sebagai sebuah kata sifat, homoseksual kini lebih sering dipahami sebagai kata benda; seorang homoseksual. Dengan kata lain, untuk memahami bahasa, kita juga membutuhkan cara berpikir yang kontekstual. Sebelum kita lebih jauh membahas bahasa, kita akan mempelajari bagaimana kajian bahasa ini mulai masuk dalam ilmu sosial, yakni lewat strukturalisme.
Bahasa dan Strukturalisme
Guna memahami strukturalisme, kita akan belajar mengenai seorang tokoh linguistik bernama Ferdinand de Saussure (1857-1913). Dalam konsep Sausurrean, dikenal istilah “sign” (tanda). Istilah “Budi”, “mimpi”, “tempe” atau “kecerdasan” merupakan contoh tanda. Dalam tanda terdapat dua hal, pertama adalah hal yang dirujuk dengan tanda tersebut atau disebut “signified” (petanda) dan suara yang digunakan untuk menyebutnya (spoken sound) atau “signifier” (penanda). “Budi” dan “tempe” memiliki kualitas konkrit, sementara “mimpi” dan “kecerdasan” tidak memiliki kualitas konkrit sebagaimana “Budi” dan “tempe”. Meskipun demikian, petanda dari keempat istilah tersebut tetap ditempatkan sebagai konsep.
Kontribusi utama Saussure adalah ia menunjukkan bahwa hubungan antara penanda dengan petanda bersifat arbitrer (manasuka) (Saussure, 2011). Sebagai contoh, kita menyebut “mouse” untuk merujuk pada binatang bernama “tikus”, tetapi kini mengatakan “mouse” bisa berarti peralatan komputer atau tetikus. Dalam menyebut kondisi emosi, orang Indonesia biasa mengatakan “gemes” (Anderson, 2016). Apakah petanda dari “gemes”? “Gemes” kita gunakan untuk menyebut seorang anak yang lucu dan menggelikan, tapi di sisi lain menyebut rasa gusar atau marah kita terhadap seseorang. Oleh karena itu, ketika Saussure mengatakan bahwa bahasa bersifat manasuka (language is arbitrary), bukan berarti bahasa merupakan sesuatu yang seenaknya saja bisa ditafsirkan (random) melainkan dengan bantuan bahasa kita membuat kategori-kategori arbitrer dalam dunia kita.
Dalam karya-karyanya, Erich Fromm (1960, 2005) membuat analisis bahwa struktur ekonomi kapitalis menciptakan pribadi-pribadi yang kompetitif. Dengan merujuk pada analisis Fromm ini, kita bisa melihat bahwa apa yang dinamakan kepribadian sangat terkait erat dengan dunia di mana kita hidup. Hal ini seringkali muncul dalam kalimat, misalnya “Dasar orang tak berkepribadian.” Dengan menyebut penanda “kepribadian” tersebut, apa petandanya?
Selain sifat hubungan antara penanda dengan petanda yang arbitrer, sumbangan lain dari Saussure adalah bahwa kita hanya bisa membedakan konsep (petanda) dengan cara menghubungkan atau mengkategorikan penanda. Misal, mengapa kita menyebut hewan berkaki empat dan menggonggong sebagai “anjing”? Mengapa bukan “kambing”? “Anjing” bisa dibedakan dengan “hewan berkaki-empat” lainnya dengan menyematkan perilaku “menggonggong”. Karena itu, bahasa tidak merefleksikan kenyataan sosial yang telah ada sebelumnya, tetapi mengkonstitusikan dan memberikan kerangka dari sebuah realitas.
Meskipun demikian, Saussure juga tidak menampik bahwa suatu penanda sangat mungkin memiliki hubungan yang tidak arbitrer dengan petanda — bahwa suatu penanda memiliki petanda atau arti tertentu yang sudah pasti. Ketika kita menyebut “anjing”, sudah menjadi kesepakatan bahwa “anjing” merupakan “hewan berkaki-empat” dan “menggonggong”. Fiksasi makna ini menjelaskan mengapa manusia bisa berkomunikasi. Seandainya hubungan antara penanda dengan petanda adalah manasuka belaka, apakah kita mungkin berbicara dengan orang lain yang memiliki bahasa privat yang sangat berbeda ketika menafsirkan suatu penanda?
Kemudian, bagaimana penanda tertentu bisa berubah seiring berjalannya waktu dan bagaimana bisa sebuah penanda memiliki petanda atau makna yang berbeda-beda tergantung siapa-yang-mengucapkan-dan-dalam-konteks-seperti-apa? Dalam konteks Indonesia, kita menemukan istilah “keluarga”. Siapa saja yang bisa disebut keluarga? Dari sudut pandang biologis, kita akan menemukan bahwa keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sejauh mana hubungan darah ini bisa menentukan seseorang adalah keluarga atau bukan keluarga kita? Apakah kakak dari nenek kita memiliki hubungan darah dengan kita? Ataukah yang dinamakan ‘keluarga’ tidak melulu konsep yang didasarkan pada hubungan biologis? Kalau memang keluarga didefinisikan dalam ranah psiko-sosiologis, sejak kapan petanda ini tercipta? Dalam sebuah penelitian etnografi yang dilakukan Shiraishi (1997/2001) di Indonesia, Anda bisa menemukan model penjelasan bagaimana penanda keluarga kemudian digunakan dalam ranah politik, sosial, dan budaya. Shiraishi (1997/2001) menjelaskan bahwa sistem keluarga yang terbentuk selama Orde Baru, dengan Soeharto sebagai supreme Father, merasuk dalam seluruh sistem dalam kelembagaan. Dalam sebuah perusahaan, sekolah, maupun kantor pemerintahan penggunaan istilah “Bapak” menjadi sangat lazim. Penggunaan istilah tersebut berimplikasi pada hirarki dalam sebuah lembaga. Persoalan korupsi konon muncul dari model bapakisme yang mana mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak — sebagaimana temuan Shiraishi.
Bagaimana dengan penggunaan istilah “Bapak” yang hadir selama Orde Baru dengan “Bapak” yang biasa kita hunakan dalam pidato? Apakah punya petanda yang sama? Berbeda dengan “Bapak” pada masa Orde Baru, “Bapak” dalam istilah pidato bukan menjadi penentu atau sumber otoritas, melainkan sekadar menjadi petanda bahwa ada orang yang dihormati tengah hadir di tengah-tengah audiens. Analisis model Shiraishi inilah yang kemudian mengantarkan kita pada kaitan bahasa dengan post-strukturalisme.
Bahasa dan Post-Strukturalisme
Post-strukturalisme merujuk pada kajian yang dilakukan setelah era Saussure. Alih-alih menyangkal gagasan Saussurean soal bahasa, post-strukturalisme menambahkan gagasan terkait bahasa. Dalam post-strukturalisme, makna atau petanda yang termuat dalam bahasa tidak pernah menetap (fixed), selalu terbuka terhadap pertanyaan, selalu dapat dibantah (contestible), dan bersifat temporer.
Ada dua kesamaan antara strukturalisme dengan post-strukturalisme. Pertama, baik strukturalisme maupun post-strukturalisme melihat bahasa sebagai arena utama dalam konstruksi manusia (as a person). Bagaimana Anda menjadi seseorang, pengalaman Anda, dan kepribadian Anda merupakan efek bahasa. Tiga kategori psikologi berupa pikiran (kognitif), perasaan (afektif), maupun tindakan (psikomotorik) merupakan produk atau fungsi dari bahasa. Bahasa merupakan fenomena sosial yang kemudian berimplikasi bahwa proses konstruksi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang individu.
Gagasan bahasa sebagai fenomena sosial ini mengantarkan pada poin persamaan kedua, yakni anti-humanisme. Humanisme dipahami sebagai rangkaian asumsi mengenai manusia (human being) bahwa manusia bersifat manunggal, koheren, dan merupakan agen rasional yang mampu menentukan pengalaman dan maknanya sendiri (logika humanis liberal). Dalam perspektif konstruksionisme sosial, humanisme dianggap sebagai sesuatu yang esensialis yang mana mengasumsikan bahwa ada esensi manusia yang unik, koheren, dan tidak berubah (misalnya soal kepribadian). Dengan menekankan sentral pada bahasa, maka konstruksionisme sosial memindahkan pusat psikologis dari individu ke dunia sosial (dikenal dengan sebutan Copernican shift). Implikasinya, ketika kita berbicara dengan seseorang maka alih-alih melihat ke dalam diri individu orang tersebut, kita perlu mengubah haluan dan memusatkan perhatian pada bagaimana ruang lingusitik membentuk diri orang termaksud.
Apabila diri merupakan produk bahasa dan interaksi sosial, maka diri tidak pernah final, selalu dalam perubahan yang terus-menerus (on-going process), serta selalu berubah tergantung dengan siapa diri tersebut berinteraksi, dalam situasi macam apa, dan dengan tujuan apa. Dengan kata lain, petanda atau makna merupakan sesuatu yang senantiasa berubah terus-menerus dan diciptakan selama proses interaksi (interactive context) (Taylor, 2001). Perubahan ini mengindikasikan bahwa apa yang dinamakan makna merupakan ruang yang penuh dengan variabilitas, ketidaksepakatan, dan berpotensi membuka ruang konflik. Oleh karena itu, post-strukturalisme melihat dunia sosial merupakan arena perjuangan dan konflik, di mana relasi kekuasaan diterapkan dan dikontestasikan.
Sebagai contoh, seorang perempuan memboncengkan seorang laki-laki. Berikut adalah percakapan antara dua orang yang tengah berada di atas motor tersebut:
Laki-laki : Coba tambah gas sedikit, kita bisa menyalip mobil di depan.
Perempuan : Iya, santuy dikitlah. Kamu diam saja, biarkan aku kendarai motor ini. Aku bisa
naik motor kok.
Laki-laki : Halah, baperan amat. Aku cuma usul kok.
Perempuan : Ya aku ndak butuh usulanmu. Biarkan aku kendarai sendiri. Percayalah
denganku, kita akan sampai kampus dengan selamat kok. Coba aku laki-laki,
pasti kamu tidak mengarahkanku seperti itu.
Laki-laki : Lhoh, maksudmu gimana? Ngajak berantem nih. Kamu selalu bilang kalau kamu
butuh bantuanku kapan hari itu. Sekarang dibantu kok malah ngomel-ngomel
ndak jelas gitu.
Perempuan : Masak kamu ndak paham sih? Seandainya aku seorang laki-laki, kamu tidak akan
menganggapku orang yang ndak bisa naik motor. Kamu cuma mau bilang kalau
perempuan ndak bisa dipercaya memboncengkan laki-laki kan?
Laki-laki : Ya elah, gimana sih kamu. Pakai bawa-bawa laki-laki dan perempuan, emang kita
lagi kuliah kajian gender ini? Ya udah sih, kalau ndak butuh usulanku ya
ndakpapa.
Diadaptasi dari Burr (1995)
Percakapan di atas menunjukkan bahwa ada makna yang tengah dikontestasikan. Baik si laki-laki maupun perempuan terlibat dalam mendefiniskan apa yang dilakukan satu sama lain dan versi pemaknaan tertentu dari masing-masing pihak. Si laki-laki menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk kebaikan hati. Sementara itu, si perempuan menilai bahwa usulan si laki-laki merupakan manifestasi dari maskulinitas laki-laki. Si laki-laki mungkin ingin menunjukkan diri bahwa dia orang yang suka menolong (helpful man). Sementara si perempuan menganggap bahwa perbuatan menolong si laki-laki merupakan representasi dari fantasi maskulin yang menempatkan perempuan butuh nasihat dan bantuan dari laki-laki.
Dalam hal ini, post-strukturalisme melihat bahwa bahasa merupakan ruang utama di mana identitas dipertentangkan atau berubah. Pertentangan atau perubahan tersebut menjanjikan bentuk dialog lewat mengenal karakter yang dikonstruksi (Gergen, 2014). Dengan demikian berbahasa merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran (consciousness-raising) dan melakukan proses transformasi.
Sebagai contoh lain adalah terkait konsep “sakit”. Konsep “sakit” seringkali diasumsikan sebagai persoalan biologis atau dikenal dengan istilah model biomedis (Burr, 2018). Namun apakah memang demikian? Ketika kita mengatakan bahwa “seseorang sedang sakit”, kita menempatkan orang tersebut tidak sekadar dalam kondisi fisiknya, tetapi juga dalam kondisi sosialnya. Figlio (1982) menunjukkan bahwa para penambang mengalami nystagmus atau kondisi pergerakan mata yang di luar kontrol sebagai ekses pekerjaannya. Kondisi fisik yang terbentuk akibat pekerjaan ini juga dialami buruh perempuan di Malaysia. Dalam pabrik-pabrik di Malaysia, para buruh perempuan secara periodik mengalami kesurupan (Ong, 1987/2010). Model “sakit” sebagaimana dijelaskan Figlio (1982) maupun Ong (1987/2010) merupakan bentukan dari sistem kapitalisme. Ong (1987/2010) menunjukkan bahwa transisi dari masyarakat petani menuju produksi industrial atau ekonomi pasar memunculkan disrupsi, konflik, dan ambivalensi posisi dalam kehidupan perempuan Malaysia. Penelitian etnografis Ong berupaya melakukan rekonstruksi gender dalam perubahan jaringan agensi dan dominasi dalam keluarga, sistem kerja, nilai dan sistem keagamaan, serta masyarakat yang lebih luas. Posisi para buruh perempuan ini, yang mana mereka menunda pernikahan sekaligus berada di bawah keketatan norma keagamaan, menciptakan tegangan tersendiri yang muncul dalam bentuk kesurupan. Dalam contoh tersebut, apa yang disebut “sakit” tidak lagi bisa dianggap persoalan biomedis, tetapi lebih pada simbol yang terkondensasikan dan tak terperikan dalam tegangan antara tanggung jawab lokal (keluarga) dan global (industri). Temuan Ong (1987/2010) tersebut menunjukkan bahwa kedirian seseorang secara sosial dikonstruksi (lihat kembali bab asumsi dasar) dan konstruksi tersebut berakar pada bahasa; “bagaimana Anda menjadi laki-laki”, “bagaimana Anda menjadi perempuan”, “bagaimana Anda menjadi anggota kelompok etnis tertentu”, dan seterusnya.
Daftar Acuan
Anderson, B. (2016). A life beyond boundaries. London & New York: Verso.
Berger, P. & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. New York: Doubleday and Co.
Burr, V. (1995). An introduction to social constructionism. London & New York: Routledge
Burr V. (2018) Social cnstructionism. Dalam P. Liamputtong (ed.) Handbook of research methods in health social sciences. Springer: Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2779-6_57-1
Burr, V. & Dick, P. (2017). Social constructionism. Dalam B. Gough (ed.), The Palgrave handbook of critical social psychology (hlm. 59-80). London: Palgrave Macmillan
De Saussure, F. (2011). Course in general linguistics. Columbia: Columbia University Press.
Figlio, K. (1986). How does illness mediate social relations? Workmen’s compensation and medicolegal practices 1890–1940. Dalam P. Wright & A. Treacher (ed.), The problem of medical knowledge (hlm. 174-224). Edinburgh: Edinburgh University Press.
Fromm, E. (1960). Fear of freedom. London: Routledge & Kegan Paul.
Fromm, E. (2005). Marx’s concept of man. London & New York: Continuum
Gergen, K. (2014). Social constructionism. Dalam T. Teo (ed.), Encyclopedia of critical psychology (hlm. 1772-1776). New York: Springer-Verlag.
Keucheyan, R. (2013). The left hemisphere: Mapping critical theory today. London & New York: Verso.
Oetomo, D. (1996). Gender and sexual orientation in Indonesia. Dalam L. J. Sears (ed.), Fantasizing the feminine in Indonesia. Durham & London: Duke University Press.
Ong, A. (1987/2010). Spirits of resistance and capitalist discipline: Factory women in Malaysia (second edition). Albany: State University of New York Press.
Saraswati, L.A. (2019). Putih: Warna kulit, ras, dan kecantikan di Indonesia transnasional. Serpong: Marjin Kiri.
Shiraishi, S.S. (2001). Pahlawan-pahlawan belia: Keluarga Indonesia dalam politik. Jakarta: Nalar.
Taylor, S. (2001). Locating and conducting discourse analytic research. Dalam M. Wetherell, S. Taylor, & S.J. Yates, Discourse as data: A guide for analysis. London: Sage.
Žižek, S. (2016). Language, violence and nonviolence. International Journal of Žižek Studies, 2(3), hlm. 1-12.

Editor Nalarasa pada rubrik Teori. Sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.